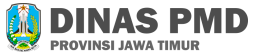UU Desa dan Kemandirian Pemdes
Undang-Undang No.6 Tahun 2014, diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa, mulai dari sosial, budaya dan ekonomi. Menurut Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, Drs H Zarkasi, M.Si., dengan UU No.6 Thn 2014, memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
“Dengan UU tersebut, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, mempercepat
pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa,” tuturnya.
Dan, yang tak kalah pentingnya, menurut Drs H Zarkasi, M.Si., UU tersebut akan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.
Sebelumnya, perjuangan menuntut otonomi desa seakan menemukan hasil ketika spirit otonomi daerah (yang menjadi amanat gerakan reformasi) termanifestasi dalam sebuah undang-undang (UU), yakni UU No.32 tahun 2004. Dalam UU tersebut disinggung pula perihal
pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai
salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi
itu ada di level PP dan bukan UU.
Definisi desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.
PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut. Pertama, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes). Ketiga, Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Keempat, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
Kelima, Membina kehidupan masyarakat desa. Keenam, Membina perekonomian desa. Ketujuh, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kedelapan, Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kesembilan, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32/2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dapat disimpulkan, baik UU No.32/2004 maupun PP No. 72 /2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Selain itu, PP 72/2005 juga melegitimasi peran BPD sebagai lembaga representatif rakyat desa untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Tetapi, PP itu tetap memunculkan masalah terkait peran BPD. PP itu masih memposisikan kewenangan BPD di bawah pemerintah desa.
Hal itu tampak pada pasal 29 yang menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, bagi Pemerintah Desa, selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa, era otonomi daerah juga mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.
Hanya dengan kesiapan itulah desa-desa di negeri ini dapat diharapkan bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sesejahtera.
Hal ini tampak mudah, mengingat regulasi yang ada telah memberikan otoritas bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Namun, pelaksaanaan otoritas itu tidaklah seperti yang diharapkan. Kenyataannya, otoritas kepala desa masih sering terpotong oleh kewenangan pemerintah kabupaten atau bupati. Kini, untuk mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari pemerintah kabupaten.
Realitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah minimnya anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal program kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan
hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan
pembangunan desa.
Sementara itu, suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan
pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya ‘sisa-sisa’ penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota.
Namun, tetap saja desa membutuhkan aliran dana dari pemerintah/pemprov/pemkab. Sebab, mengandalkan pendapatan asli desa saja tidak akan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, bahkan dalam standar minimum sekalipun. Hal inilah yang sesungguhnya menimbulkan ketidakmandirian desa dalam segala aspek. Ketiadaan alokasi khusus anggaran dari negara untuk desa menyebabkan desa
mesti berebut ‘remah-remah’ dana pembangunan.
Ketidakmandirian dalam aspek lainnya juga terlihat dalam mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam mekanisme tersebut, pihak desa hanya bisa memberikan usulan-usulan dan aspirasi tertentu guna kepentingan pembangunan desa. Sementara, implementasinya (yang sangat terkait erat dengan pendanaan) harus menunggu ‘kebaikan hati’ pemerintah Kabupaten. Hal ini juga disebabkan ketergantungan desa pada sokongan finansial desanya. (yad)